Penulis: Dr. Sufrin Efendi Lubis, Lc., M.A
Terdapat sedikit kesulitan ketika melihat padanan kata bahagia dalam bahasa Arab khususnya di dalam Al-Qur'an. Ragam istilah ini dapat dipetakan kepada dua bagian umum, yaitu istilah yang menunjukkan makna bahagia secara langsung dan istilah yang menunjukkan makna bahagia secara tidak langsung. Istilah-istilah yang menunjukkan bahagia secara langsung adalah: falah, fauz, sa’adah, farah dan surur, sementara istilah yang menunjukkan makna bahagia secara tidak langsung adalah: thuba, busyra, thayyib, hasanah, barakah dan salam.
Ragam istilah ini tidak lepas dari dua kemungkinan, pertama karena keterbatasan bahasa Indonesia di dalam mengungkap makna istilah-istilah tersebut, kedua karena ini merupakan bahasa wahyu yang kaya dengan makna dimana masing-masing istilah memiliki penekanan makna yang berbeda dengan istilah lain. Sebagai contoh istilah falah dan fauz. Sepintas, kata-kata ini terlihat semakna, namun apabila dicermati setiap kata memiliki penekanan dan fokus yang berbeda. Sebagai contoh, apabila kata falah menunjukkan kebahagiaan yang diperoleh setelah melalui banyak rintangan dan tantangan, maka fauz adalah kebahagiaan yang diperoleh dengan anugerah meskipun tidak harus melalui rintangan atau tantangan.
Di sisi lain, makna falah adalah kebahagiaan yang akan didapatkan di dunia dan di akhirat, berbeda dengan fauz yang hanya menitikberatkan makna bahagia pada kehidupan akhirat saja. Hal ini senada dengan pandangan dari Al-Raghib al-Asfahani dalam kitabnya Mufradat Al faz Al-Qur’an, bahwa makna falah dalam artian kebahagiaan terbagi menjadi dua bagian, yaitu: pertama kebahagiaan yang berurusan dengan hal-hal keduniaan dan yang kedua yaitu kebahagiaan yang berurusan dengan hal-hal akhirat. Adapun fauz merupakan kebahagiaan yang mengarah pada terpenuhinya janji Allah terhadap orang yang beriman dan bertakwa berupa surga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya serta mendapat keridhaan-Nya.
Perbedaan antara keduanya semakin jelas, khususnya setelah melihat makna asal dari setiap masing-masing kata. Bahwa makna dasar kata falah adalah membelah atau memotong, seolah-olah mereka memotong berbagai kesulitan yang hampir menghambat dalam proses meraih kebahagiaan tersebut. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Abdul Jabbar dan Burhanuddin bahwa falah memiliki arti dasar membelah atau memotong. Oleh karena itu, bahasa Arab seorang petani disebut dengan fallah merupakan derivasi dari falah juga, karena pekerjaan mereka adalah memotong tanah atau mencangkul (Ensiklopedia Makna al Quran Syarah Alfaazhul Quran, 2012). Sementara itu, makna dasar dari kata fauz adalah binasa yang mengandung arti bahwa kebahagiaan yang akan manusia dapatkan setelah ia binasa atau mati yakni kebahagiaan akhirat.
Berangkat dari ragam istilah yang digunakan Al-Qur'an untuk menyebut kebahagiaan maka penulis menganggap penting untuk melihat hakikat kebahagiaan yang sesuai dengan pandangan Islam serta bagaimana supaya kebahagiaan ini dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Artinya, untuk mendapatkan kebahagiaan, individu harus mengawalinya dengan pengenalan terhadap apa itu kebahagiaan, skema kebahagiaan menurut Islam, kemudian langkah-langkah konkrit untuk menginternalisasikan kebahagiaan tersebut dalam kehidupan.
Berdasarkan hasil penelusuran, penulis melihat bahwa ada dua kata kunci kebahagiaan dalam Islam, yaitu sikap/penyikapan dan pemahaman. Pertama sikap/penyikapan, bahwa kebahagiaan dalam Islam bukan dari wujud yang ada dan bukan pula dari apa yang dimiliki, kebahagiaan itu justru ditentukan oleh sikap dan penerimaan terhadap keadaan. Meskipun Ibnu Miskawaih menjadikan aspek materi sebagai salah satu ukuran kebahagiaan, namun pada hakikatnya sikap dalam menerima materi itulah yang jadi ukuran kebahagiaan. Artinya, orang yang menggantungkan kebahagiaan kepada materi adalah keliru, ingin bahagia dengan mengejar materi juga kesalahan. Prinsip yang benar adalah kebahagiaan ditentukan oleh sikap/penyikapan, dan sikap/penyikapan ini tidak terikat dengan benda dan materi, bahwa materi bukan musuhnya kebahagiaan dan kebahagiaan dapat berdamping dengan materi dan kebendaan, hanya saja ia bukan ukuran kebahagiaan.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kebahagiaan tidak dinilai dari lengkapnya fasilitas yang dimiliki namun lebih menekankan pada penerimaan dengan realitas kehidupan, sehingga ia tidak membandingkan apalagi sampai harus memiliki setiap yang dimiliki orang lain. Orang yang merasa cukup maka akan diberi kecukupan (kebahagiaan) baginya (HR. Bukhari dan Muslim). Ridha dengan yang dibagikan Allah SWT., untukmu, niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya (HR. Tirmidzi). Oleh Karena itu, kebahagiaan belum tentu didapatkan pada banyaknya materi yang dimiliki, sesuai dengan nasehat Rasulullah dalam sebuah hadits “Yang namanya kaya (ghina') bukanlah dengan banyaknya harta (atau banyaknya kemewahan dunia). Namun, yang namanya ghina' adalah hati yang selalu merasa cukup.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Kunci kedua adalah pemahaman. Pemahaman yang benar tentang konsep kebahagiaan adalah kunci penentu untuk mewujudkan kebahagiaan. Dalam kontesk ini, hakikat kebahagiaan terletak pada pemahaman individu tentang kehidupan itu sendiri. Individu yang meyakini sepenuh hati bahwa selain kehidupan dunia masih ada kehidupan akhirat yang abadi tentu akan menjadikan akhirat sebagai orientasi tindakan dan perbuatan. Individu juga akan menjadikan akhirat sebagai parameter dalam menentukan pilihan bahkan tindakan, sehingga jangan sampai karena mengejar kehidupan dunia justru mendapatkan kesengsaraan di akhirat. Hal ini sesuai dengan pandangan Ghazali yang lebih menekankan esensi kebahagiaan dengan kondisi jiwa. Menurutnya, kebahagiaan berfokus pada pengenalana manusia terhadap Allah dan kekuasan-Nya serta bagaimana manusia menyikapinya.
Sikap berbeda tentu akan datang dari seorang yang hanya menjadikan kehidupan dunia sebagai satu-satunya ukuran kebahagiaan. Implikasi dari pemahaman bahwa dunia sebagai satu-satunya ukuran kebahagiaan, maka kebahagiaan hanya milik kalangan tertentu dan di waktu tertentu. Disebut kalangan tertentu karena kaitannya dengan kepemilikan dan kepunyaan, dan disebut di waktu tertentu karena kebahagiaan hanya akan dapat kalau sesuai dengan keinginan dan harapan. Anggapan ini tentu tidak sejalan dengan konsep kebahagiaan yang ditawarkan Islam, dimana kebahagiaan ditentukan oleh sikap dan tingkat pemahaman, bukan oleh kepemilikan dan kesesuaian dengan harapan.
Di antara argumentasi teologis bahwa kebahagiaan ditentukan oleh sikap dan benarnya pemahaman adalah firman Allah SWT., dalam QS. At-Taubah: 51: “Katakanlah (Muhammad), “Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakalnya orang-orang yang beriman.” Sementara itu, bukti Hadits sebagai pedoman dapat dilihat dari riwayat Sahabat Shuhaib, dia berkata, bahwa Rasulullah SAW., pernah bersabda: “Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya.” (HR. Muslim, no. 2999).
Ayat 51 dari surah At-Taubah di atas menjelaskan bahwa apapun yang menimpa individu manusia semata-mata karena kehendak Allah SWT. Dalam konteks teologis, manusia tidak bisa menghindar dari takdir baik dan takdir buruk. Menurut Umar bin Al Khattab: “Kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain,” (Imam Al-Bukhari: 28). Oleh karena itu, sesungguhnya hakikat kebahagiaan bukan pada jenis takdir yang diterima individu manusia, melainkan bagaimana individu dalam menyikapi takdir tersebut. Dengan demikian, takdir baik seperti kepemilikan materi, sumber usaha yang mumpuni atau status sosial yang tinggi, apabila tidak disikapi dengan cara yang baik justru menjadi penyebab seorang individu gelisah, kecewa, dan tidak akan mendapatkan kebahagiaan.
Namun sebaliknya, ketika takdir buruk seperti kekurangan materi, sumber usaha yang tidak pasti, dan status sosial rendah, disikapi bijaksana sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits, justru akan menjadikan individu tersebut dalam keadaan kedamaian dan ketentraman. Inilah maksud dari Hadits Rasulullah SAW., dari Sahabat Shuhaib ra., bahwa seorang muslim dalam situasi apapun selalu bahagia, karena kebahagiaan sejatinya bukan pada kepemilikan namun pada penyikapan.
Pada prinsipnya, konsep kebahagiaan yang ditawarkan para pemikir muslim memiliki beberapa kesamaan. Persamaan paling signifikan yaitu pada puncak dari kebahagiaan itu sendiri, yaitu kebahagiaan akhirat yang abadi di saat seorang hamba diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Allah SWT., berfirman: … Barangsiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. (QS. Ali 'Imran: 185).








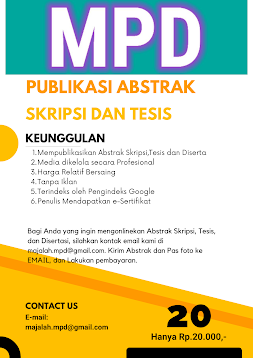








.jpg)
0 Komentar
Silakan tinggalkan komentar Anda